Pendidikan
Postkolonialisme Digital dan Tantangan Kemerdekaan Teknologi
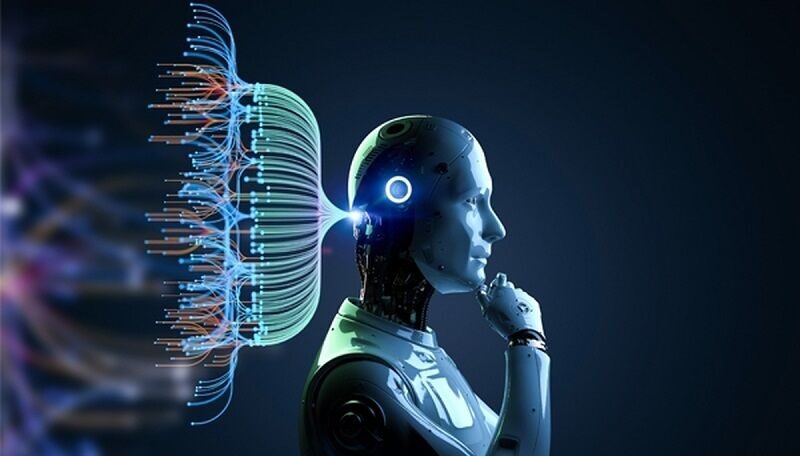
Ahlulbait Indonesia, 26 Desember 2025 — Di tengah meningkatnya krisis kemanusiaan global dan percepatan adopsi teknologi canggih, muncul peringatan serius tentang bentuk baru dominasi global yang bekerja secara halus namun sistemik: teknokolonialisme. Fenomena ini menempatkan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (IA) dan big data, bukan semata sebagai instrumen kemajuan, melainkan sebagai sarana kekuasaan baru yang berpotensi mereproduksi ketimpangan global.
Peneliti dan dosen universitas, Manucher Manouchehr, dalam sebuah artikel yang dipublikasikan kantor berita IRNA, menyoroti kenyataan bahwa lebih dari 300 juta orang di dunia saat ini membutuhkan bantuan kemanusiaan, sementara bencana iklim dan krisis sosial terus meningkat. Dalam kondisi tersebut, teknologi mutakhir kerap dipromosikan oleh kekuatan global dan lembaga internasional sebagai “alat kebaikan” dan solusi universal. Namun, di balik narasi kemanusiaan itu, terbentuk pola dominasi lunak berbasis data, algoritma, dan infrastruktur digital.
Menurut Manouchehr, dalam logika teknokolonialisme, data manusia, terutama dari negara-negara Global South, telah berubah menjadi sumber daya strategis baru bagi negara-negara maju. Teknologi biometrik, platform kecerdasan buatan, dan analitik big data banyak diterapkan di kamp pengungsi serta wilayah krisis. Alih-alih memberdayakan masyarakat lokal, teknologi tersebut kerap berfungsi sebagai sarana kontrol, pengawasan, dan laboratorium uji coba algoritma, yang pada akhirnya memperdalam apa yang oleh para peneliti disebut sebagai “ketidaksetaraan digital”.
Ia menjelaskan bahwa teknokolonialisme merupakan perpanjangan dari logika kolonialisme klasik yang kini beroperasi di lapisan tersembunyi infrastruktur digital. Jika pada abad ke-19 sumber daya alam dijarah melalui pendudukan fisik, maka pada era kini yang diekstraksi adalah data dan kecerdasan manusia. Proses ini berlangsung dengan wajah yang lebih rapi, dibungkus filantropi, inovasi, dan bantuan global, namun dampak strukturalnya tetap serupa.
Menghadapi realitas tersebut, Manouchehr menekankan pentingnya membangun kesadaran kritis terhadap struktur kekuasaan di dunia digital. Pembebasan dari dominasi tersembunyi ini, menurutnya, harus dimulai dari pemahaman yang jujur atas realitas, menuju kebenaran, dan pada akhirnya diarahkan pada cita-cita kemanusiaan serta nilai-nilai Ilahiah. Teknologi, dalam kerangka ini, tidak dapat diposisikan sebagai entitas netral, melainkan harus ditautkan secara sadar dengan etika, keadilan, dan iman guna mengekang potensi dominasi dari dalam sistem itu sendiri.
Dalam konteks yang lebih luas, ia mengajukan gagasan tentang demokrasi religius yang dipadukan dengan teknokratisme berbasis keyakinan sebagai model pemerintahan alternatif yang cerdas dan beretika. Model ini menuntut peran aktif para insinyur, ilmuwan, dan kaum terdidik dalam merancang pilar kemerdekaan teknologi dan keadilan digital. Peran politisi, tegasnya, bukan untuk merebut panggung, melainkan menyiapkan ruang dan kebijakan yang memungkinkan para teknokrat mengabdi pada demokrasi dan kepentingan publik.
Jika sinergi tersebut terwujud, dampaknya diyakini signifikan: migrasi kaum elit dapat ditekan, talenta berkembang di dalam negeri, dan teknologi bertransformasi menjadi sarana martabat serta kemajuan bangsa, bukan alat dominasi baru.
Pada akhirnya, kolonialisme digital tidak semata perlu dilihat sebagai ancaman, melainkan juga sebagai penanda kebangkitan kesadaran. Dengan pemahaman yang tepat, realitas ini dapat menjadi jembatan dari kesadaran menuju kebebasan, serta dari teknologi menuju nilai-nilai iman dan kemanusiaan. []
Sumber: IRNA

