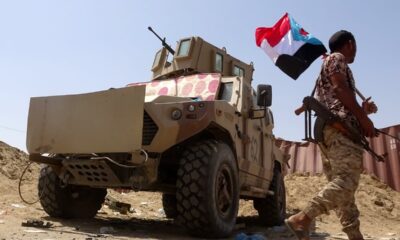Opini
Bahasa Cinta di Tengah Genosida Gaza: Strategi Digital Akun Pro-Israel di Indonesia

Ahlulbait Indonesia, 31 Desember 2025 — Saat Gaza berada dalam kehancuran dan puluhan ribu warga Palestina tewas, ruang digital Indonesia justru menghadirkan narasi tandingan. Sejumlah akun media sosial menjalankan kampanye pro-Israel secara konsisten, membingkai konflik melalui pesan-pesan kemanusiaan, sambil mengaburkan konteks pendudukan, apartheid, dan genosida yang tengah berlangsung.
Fenomena ini tidak muncul dalam ruang hampa. Di tengah meningkatnya perhatian global terhadap perang dan genosida Israel di Gaza, ruang digital Indonesia, salah satu ekosistem media sosial terbesar di dunia Muslim, menjadi medan strategis dalam perebutan opini publik. Tulisan ini berdasarkan pemantauan konten media sosial dan diskursus daring, merujuk pada laporan Middle East Monitor yang dimuat pada 30 Desember 2025, karya Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat berjudul: “On @israellovesindonesia and Israel’s Growing Online Campaign in Indonesia”.
Normalisasi Tanpa Diplomasi
Laporan tersebut menelusuri bagaimana kampanye digital pro-Israel beroperasi secara sistematis di Indonesia, bukan melalui diplomasi resmi, melainkan lewat proses normalisasi bertahap di tingkat publik. Strategi soft power ini menjadi signifikan karena Indonesia, secara historis dan politik, dikenal sebagai salah satu pendukung paling konsisten perjuangan Palestina.
Menurut laporan itu, dalam beberapa bulan terakhir, Muhammad Zulfikar Rakhmat melakukan penelusuran terhadap pola penyebaran narasi pro-Israel di media sosial Indonesia. Dari pemantauan tersebut, muncul satu akun yang dinilai representatif dari strategi yang lebih luas. Akun ini tidak berdiri sendiri, melainkan beroperasi seiring dengan berbagai inisiatif digital lain yang bertujuan membentuk ulang persepsi publik. Normalisasi didorong bukan melalui perdebatan terbuka atau jalur diplomasi formal, tetapi melalui pengulangan pesan, manipulasi emosi, dan penghilangan konteks secara sistematis. Akun Instagram dan Facebook @israellovesindonesia menjadi salah satu contoh yang paling menonjol.
Secara kuantitatif, akun tersebut tampak berada di pinggiran. Berdasarkan penelusuran data publik, akun ini aktif sejak Agustus 2020 dan telah memublikasikan lebih dari 1.600 unggahan di Instagram, dengan sekitar 1.114 pengikut. Tingkat keterlibatan relatif rendah; jumlah tanda suka umumnya tidak melampaui 50, sementara kolom komentar sering kali sepi. Ketika diskusi muncul, sejumlah pengguna Indonesia secara terbuka menyebut akun ini sebagai “buzzer”, istilah yang lazim digunakan untuk menggambarkan propaganda terkoordinasi. Akun Facebook-nya, dengan sekitar 1.000 pengikut, menunjukkan jangkauan yang serupa terbatasnya.
Namun, pengaruh kampanye digital tidak selalu diukur melalui besarnya audiens. Sejumlah peneliti komunikasi politik dan pengamat disinformasi digital menekankan bahwa kampanye semacam ini bekerja melalui konsistensi dan pengulangan jangka panjang, bukan melalui viralitas sesaat.
Dilihat dari pola unggahan, tujuan utama @israellovesindonesia tampaknya bukan membujuk publik Indonesia secara instan, melainkan secara perlahan mengikis resistensi moral dan politik. Akun ini secara rutin menyebarkan berita positif tentang Israel dari media arus utama, menyoroti kemajuan di sektor pertanian dan teknologi, serta mendorong Indonesia untuk menandatangani apa yang mereka sebut sebagai “Perjanjian Perdamaian Bersejarah”.
Dari Kemanusiaan yang Dikurasi ke Emosi Politik
Sebelum Oktober 2023, konten akun tersebut didominasi visual koeksistensi yang dikurasi secara cermat. Entitas Israel Yahudi digambarkan memberikan bantuan medis, menyampaikan ucapan Ramadan, atau terlibat dalam kegiatan sosial. Dalam kajian komunikasi politik, pendekatan semacam ini dipahami bukan sebagai pesan netral, melainkan sebagai upaya memisahkan citra negara dari kebijakan strukturalnya, dengan menggantikan realitas pendudukan melalui representasi kemanusiaan.
Perubahan tajam terjadi setelah Oktober 2023. Ketika Gaza mengalami kehancuran masif dan puluhan ribu warga Palestina tewas, sementara tindakan Israel semakin banyak dikategorikan oleh pakar hukum internasional, organisasi hak asasi manusia, serta sejumlah negara sebagai genosida, nada akun ini ikut bergeser. Unggahan menjadi lebih emosional, menonjolkan narasi mengenai sandera Israel yang diklaim diambil oleh Hamas, sembari menghilangkan konteks yang lebih luas mengenai pengepungan, apartheid, dan genosida yang berlangsung.
Normalisasi dan Erosi Kompas Moral
Dalam fase ini, akun tersebut juga mulai secara terbuka mendukung langkah geopolitik Israel, termasuk pengakuan terhadap Somaliland, sebuah kebijakan yang oleh banyak analis hubungan internasional dinilai berpotensi destabilisatif dan sarat kepentingan politik.
Di Facebook, dampak dari pesan-pesan ini mulai terlihat lebih jelas. Sebuah unggahan yang mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, mengenai Gaza yang tidak boleh dibangun kembali sebelum Hamas dilucuti, memicu komentar yang secara eksplisit membenarkan hukuman kolektif. Sejumlah pengguna menyebut pembangunan kembali Gaza sebagai pemborosan dan menjustifikasi penghancuran wilayah tersebut selama Hamas belum “dimusnahkan”.
Bagi pengamat wacana politik, respons semacam ini menunjukkan bagaimana normalisasi bekerja dalam praktik. Genosida dibingkai ulang sebagai kebijakan keamanan, penghancuran massal warga sipil diposisikan sebagai rasionalitas pragmatis, dan kehidupan warga Palestina direduksi menjadi variabel yang dapat dikorbankan.
Pola serupa muncul dalam unggahan lain terkait kebijakan Afrika Selatan yang mencabut visa sejumlah warga Palestina. Kolom komentar dipenuhi penghinaan bernuansa agama serta praktik whataboutism, yakni pengalihan isu untuk menghindari pertanggungjawaban substantif. Dalam kajian kejahatan internasional, strategi retorika semacam ini kerap menyertai kekerasan sistemik karena memungkinkan kekejaman diremehkan dan dinormalisasi.
Sejumlah peneliti mencatat bahwa akun-akun semacam ini jarang muncul secara organik. Mereka umumnya terhubung dengan jaringan kampanye yang lebih luas, termasuk inisiatif seperti The Peace Factory yang didirikan oleh desainer grafis Israel, Ronny Edry. Sejak 2012, Edry dikenal luas di media Barat dengan gagasan perdamaian berbasis pesan antarmasyarakat.
Namun, banyak akademisi mengingatkan bahwa perdamaian yang dilepaskan dari kebenaran struktural berisiko berubah menjadi propaganda. Kampanye semacam ini cenderung menghapus relasi kuasa dari percakapan, menghilangkan pendudukan, apartheid, dan genosida, lalu menggantikannya dengan seruan abstrak tentang empati dan dialog.
Batas Moral Normalisasi
Bagi Indonesia, persoalan ini memiliki dimensi historis dan konstitusional. Dukungan terhadap Palestina berakar pada prinsip penolakan terhadap kolonialisme dalam segala bentuknya, sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan dibentuk melalui pengalaman penjajahan. Dalam kerangka ini, normalisasi hubungan dengan Israel ketika rakyat Palestina hidup di bawah pendudukan, apartheid, dan genosida dipandang oleh banyak kalangan bukan sebagai realisme politik, melainkan sebagai kegagalan moral.
Perdamaian tidak dapat dibangun di atas narasi media sosial yang dikurasi di tengah kehancuran. Normalisasi tidak menjadi etis hanya karena dibungkus bahasa cinta dan kemanusiaan. Justru karena sifatnya yang senyap, konsisten, dan disiplin, ofensif soft power semacam ini perlu dicermati secara kritis. Jika tidak, ketidakadilan, bahkan genosida berisiko direduksi menjadi semata persoalan perbedaan sudut pandang, lalu perlahan diterima sebagai kewajaran. [HMP]
Sumber: Middle East Monitor