Opini
KUHP Baru: Ujian Negara Hukum dan Masa Depan Perlindungan Warga
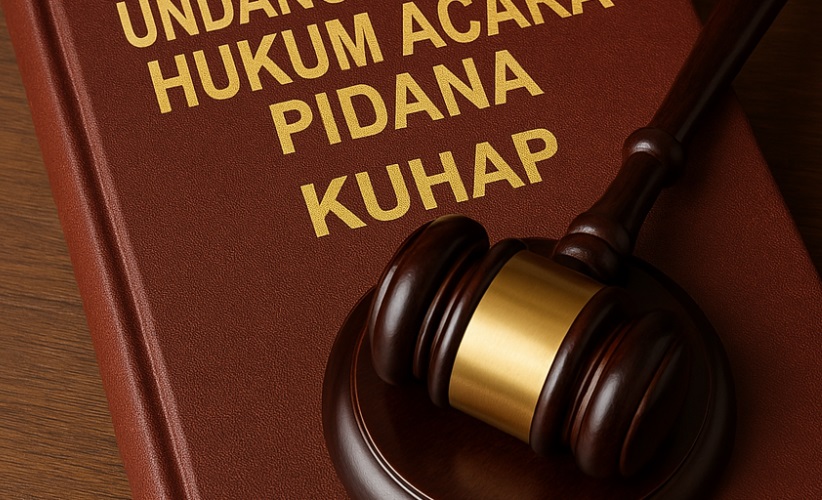
Jakarta, 4 Januari 2026 — Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional secara resmi mulai berlaku pada Jumat, 2 Januari 2026. Pemberlakuan ini berjalan bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Momentum tersebut menandai babak baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia, sekaligus menjadi ujian krusial bagi komitmen negara terhadap prinsip negara hukum serta perlindungan hak-hak warga negara.
Pemerintah memposisikan KUHP Nasional sebagai pembaruan fundamental yang dirancang agar selaras dengan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai bangsa Indonesia, menggantikan hukum pidana warisan kolonial yang selama puluhan tahun dinilai semakin kehilangan relevansinya. Sejalan dengan itu, salah satu anggota Badan Legislasi DPR RI menyebut berlakunya KUHP dan KUHAP sebagai manifestasi reformasi menyeluruh atas sistem hukum pidana nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.
Namun demikian, sejak tahap pengesahan hingga implementasinya, KUHP baru tidak pernah lepas dari sorotan kritis publik. Sejumlah ketentuan dinilai berpotensi membatasi kebebasan berpendapat, hak atas privasi, serta ruang sipil, meskipun secara formal telah dilengkapi dengan mekanisme pelaksanaan melalui KUHAP yang baru.
Di titik inilah perdebatan substantif bermula. Dalam sebuah negara hukum, persoalan utama tidak berhenti pada niat baik pembentuk undang-undang, melainkan pada bagaimana hukum tersebut beroperasi ketika bersinggungan dengan relasi kuasa antara negara dan warga negara. Kontroversi seputar KUHP baru tidak lahir dari penolakan terhadap kebutuhan pengaturan, melainkan dari kekhawatiran bahwa sejumlah pasalnya berpotensi menggeser ulang keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak warga dengan cara yang belum sepenuhnya menjamin rasa aman.
Dengan demikian, persoalan mendasarnya bukan semata apa yang hendak diatur, melainkan arsitektur kekuasaan yang dibangun melalui rumusan norma, ruang tafsir yang tersedia, serta mekanisme penegakan hukum yang akan menentukan wajah keadilan di masa mendatang.
Norma Kabur dan Risiko Tafsir Subjektif
Salah satu persoalan mendasar dalam KUHP baru adalah penggunaan istilah yang longgar dan elastis: “penghinaan”, “kepentingan umum”, “keresahan”, “paham yang bertentangan”, atau “hukum yang hidup”. Dalam hukum pidana, ketidakjelasan bukan hanya kelemahan redaksional. Ketidakpastian norma merupakan celah struktural yang berisiko besar.
Bayangkan satu ilustrasi sederhana, misalnya seorang warga menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam sebuah forum terbuka. Kritik tersebut tidak menyerukan kekerasan, tetapi memancing kemarahan sekelompok pendukung kebijakan hingga terjadi ketegangan. Dalam situasi seperti ini, kritik dapat ditafsirkan sebagai “penghinaan”, reaksi massa dibaca sebagai “keresahan”, dan rangkaian peristiwa itu dijadikan dasar pemidanaan. Persoalannya bukan pada kritik itu sendiri, melainkan pada rantai tafsir yang sepenuhnya bergantung pada sudut pandang aparat.
Ketika norma tidak presisi, keadilan berpindah dari teks hukum ke subjektivitas penegak hukum. Akibatnya, kepastian hukum melemah, dan warga tidak lagi berhadapan dengan aturan yang jelas, melainkan dengan kemungkinan tafsir yang berubah-ubah.
Diskresi Aparat dan Asimetri Kekuasaan
KUHP baru memberikan ruang diskresi yang luas kepada aparat penegak hukum. Diskresi memang bagian dari praktik penegakan hukum. Namun diskresi tidak pernah netral secara sosial, sebab kewenangan ini selalu bekerja dalam relasi kuasa yang timpang.
Dalam kenyataan, diskresi lebih sering berdampak pada aktivis, jurnalis, kelompok minoritas, dan warga tanpa perlindungan politik. Norma yang sama, dengan ruang tafsir yang sama, jarang menghasilkan konsekuensi setara bagi elite politik atau ekonomi. Di sinilah problem struktural muncul, dimana diskresi tanpa pagar yang ketat hampir selalu bergerak ke bawah, bukan ke atas.
Ruang Tafsir Politik dan Pelajaran Sejarah
Pasal-pasal yang berkaitan dengan ideologi, legitimasi pemerintah, agama, dan ketertiban umum memiliki karakter khusus karena mudah ditarik ke dalam kepentingan politik. Ini bukan tudingan personal, melainkan pelajaran sejarah yang berulang.
Pengalaman menunjukkan bahwa pasal-pasal ideologis dan moral paling aktif digunakan pada masa ketegangan politik dan polarisasi sosial. Dalam situasi semacam itu, hukum pidana berisiko bergeser dari instrumen keadilan menjadi alat stabilisasi kekuasaan. Negara hukum yang sehat tidak hanya bergantung pada niat baik penguasa, tetapi pada desain hukum yang secara sistematis membatasi potensi penyalahgunaan.
Pidana sebagai Jalan Terakhir, Bukan Refleks Pertama
Prinsip ultimum remedium merupakan fondasi etik hukum pidana modern. Hukum pidana digunakan ketika mekanisme sosial, administratif, dan perdata tidak lagi memadai. Dalam KUHP baru, pada sejumlah pasal, pidana justru tampil terlalu dini sebagai respons atas ekspresi, relasi privat, dan dinamika sosial.
Negara yang terlalu cepat memidanakan warganya sejatinya sedang mengakui kegagalan instrumen non-represif yang dimiliki. Ketertiban yang dibangun dengan ancaman pidana mungkin tampak rapi di permukaan, tetapi menyimpan ketegangan laten. Demokrasi tidak tumbuh dari rasa takut, melainkan dari kepercayaan.
Dalam kerangka ini, hukum pidana idealnya berfungsi seperti pisau bedah, tajam, presisi, dan digunakan secara hemat. Ketika fungsi tersebut berubah menjadi pisau serbaguna, fleksibel namun tidak selektif, dan yang paling sering terluka bukanlah kekuasaan, melainkan warga biasa.
Masukan Kebijakan: Dari Niat ke Desain yang Aman
Agar KUHP baru benar-benar menjadi fondasi negara hukum yang adil, langkah korektif perlu dipertimbangkan secara serius.
Pertama, pedoman interpretasi yang presisi dan mengikat harus segera disusun oleh otoritas yudisial dan penegak hukum untuk membatasi tafsir norma kabur.
Kedua, pengawasan efektif terhadap penggunaan diskresi aparat perlu diperkuat melalui mekanisme evaluasi yang transparan dan akuntabel.
Ketiga, keberanian melakukan koreksi melalui uji materiil atau revisi terbatas harus dipandang sebagai proses demokratis, bukan ancaman terhadap wibawa negara.
Keempat, pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan represif ke berbasis hak perlu ditegaskan dalam kebijakan dan praktik. Mengabaikan langkah-langkah ini tidak hanya berisiko yang berpotensi melahirkan pelanggaran individual, tetapi juga menciptakan preseden yang kelak sulit dikoreksi.
Penutup: Waktu sebagai Faktor Penentu
KUHP baru akan menjadi cermin masa depan negara hukum Indonesia. Peraturan pidana ini dapat menjadi fondasi keadilan yang kokoh, atau sebaliknya, menjadi catatan panjang tentang bagaimana niat baik tersandung oleh desain kekuasaan yang kurang hati-hati. Koreksi dini selalu lebih murah dan lebih sehat dibandingkan pemulihan setelah kerusakan terjadi.
Menunda pembenahan dengan alasan “menunggu praktik” berarti membiarkan risiko berubah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan menjelma menjadi preseden. Dalam negara hukum, waktu bukan hanya penanda kalender, melainkan penentu arah. Dan arah tersebut, pada titik ini, masih sepenuhnya berada dalam jangkauan kebijakan yang bijaksana. [HMP ABI]
Sumber berita: PARLEMENTARIA













